Laporan Digital Around The World yang dirilis oleh Hootsuite awal tahun 2019, menunjukkan bahwa dari total 268,2 juta jiwa penduduk Indonesia terdapat sekitar 150 juta jiwa yang merupakan pengguna Internet. Jumlah ini meningkat sekitar 13% atau naik sekitar 17 juta jiwa dibandingkan tahun 2018. Begitu juga dengan data pengguna media sosial aktif di Indonesia yang tercatat sekitar 150 juta jiwa.
Angka ini meningkat 15% atau sekitar 20 juta jiwa dari tahun 2018. Artinya, kurang lebih ada setengah dari total jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia yang memiliki akses internet dan sekaligus menggunakan media sosial secara aktif.

Statistik Pengguna Digital Dan Internet Indonesia 2019
Namun, glorifikasi statistik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Toh, ruang besar bernama media sosial memberi kesempatan pada algoritma untuk bekerja. Algoritma mengkomputasikan jejak-jejak digital dan menggiring kita untuk tahu apapun dari manapun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mulai dari informasi yang kita inginkan, sampai pada informasi yang justru hanya merugikan kita.
Di media sosial, kita bisa bersepakat dan tidak setuju dalam waktu yang bersamaan. Juga, berdebat tentang banyak hal yang sehat sampai yang paling “sakit” dengan orang yang kita kenal bahkan tidak kita kenal sekalipun. Media sosial menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan.
Pada musim pemilihan presiden di Indonesia yang lalu, misalnya. Berbagai bentuk misinformasi dan disinformasi berseliweran di sana. Demi “satu” adalah “satu”, dan “dua” adalah “dua”. Tidak banyak orang yang bisa membangun ruang toleransi. Polarisasi pun tidak terhindarkan.
Sekarang, pemilihan umum telah usai. Namun apakah “ribut-ribut” juga selesai? Jawabannya, tentu tidak. Narasi “cebong” dan “kampret” masih terus digemakan untuk memapankan pilihan masing-masing. Sungguh, media sosial adalah ruang lain yang mengamini bahwa masalah itu ada dan berlipat ganda.
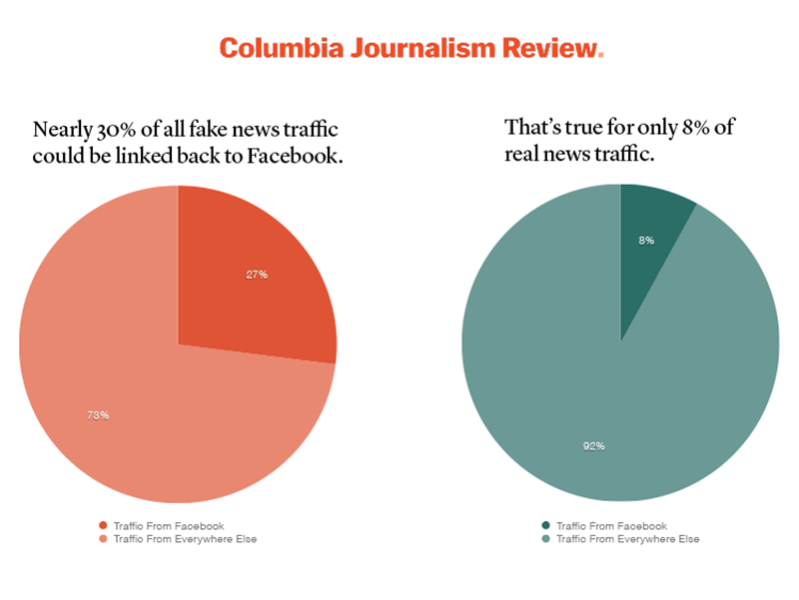
Mulai dari Pilpres, Indonesia tanpa ini dan itu, kasus penistaan agama, dan sebagainya yang dilebarkan mediumnya ke media digital membuat tidak sedikit orang yang jengah. Salah seorang kawan, misalnya. Ia bercerita tentang keputusan untuk “membisukan” semua postingan dari seorang kawannya yang “berhijrah”.
Bukan keputusan berhijrahnya yang mengganggu, melainkan menyoal tentang refleksi pemikiran yang diselesaikannya dalam beberapa karakter di media sosial. Ia menganggap postingan kawannya yang berseliweran di timeline media sosialnya terlalu penuh dengan penghakiman. Alih-alih memberikan pencerahan, postingan kawannya hanya membuat ia risih. Maka baginya, keputusan untuk membisukan notifikasi adalah pilihan paling tepat.
Keputusan semacam ini yang juga telah diulas oleh Anggela Lashbrook dalam Is it Okay to Mute Your Annoying Friends on Social Media?
Adalah Emma yang memutuskan untuk membisukan dan menghapus banyak orang dari daftar pertemanannya di media sosial. Perlakuan tidak menyenangkan yang pernah ia peroleh berimbas pada ketidaknyamanannya setiap kali melihat postingan beberapa kawannya di Facebook. Bukan hanya kisah Emma, ada juga Rose yang memutuskan untuk membisukan postingan kawannya dengan alasan pilihan politik, atau Allison yang seringkali merasa terganggu dengan postingan yang terlalu “berlebihan”.
Meskipun pada akhirnya dalam kasus di atas, Anggela Lashbrook juga mulai terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Ia mulai mempertanyakan apakah keputusan untuk membisukan dan menghapus beberapa kawan di media sosial adalah tindakan yang tepat atau bukan? Mengapa ia sampai merasa sangat terganggu dengan orang-orang yang bahkan mungkin tidak berniat untuk menganggunya?
Dalam banyak hal, keputusan-keputusan penting seperti membisukan dan menghapus orang dari daftar pertemanan justru merupakan pilihan yang sehat. Bagaimana tidak, alasan-alasan di balik keputusan itu memang lebih banyak berakar masalah.
Mulai dari merasa terganggu dengan postingan yang terlalu sering muncul, foto-foto liburan dan prestasi kawan-kawan yang lain, konten yang dianggap menghakimi hingga menjatuhkan, pembahasan tentang topik yang secara personal dianggap tidak menarik, atau pada sebagian orang yang menganggap bahwa berbeda pilihan politik juga adalah masalah, hingga pada postingan yang melanggengkan ingatan akan pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu.
Apapun alasannya, untuk kita yang “membawa” media sosial kemanapun kita pergi, satu hal yang perlu kita resapi adalah kita memiliki otoritas untuk bertanggung jawab pada hidup seperti apa yang ingin dilihat, juga pada kebahagiaan yang seperti apa ingin kita raih. Meskipun konsep tentang kebahagiaan adalah subjektif.
Bukan hanya itu, pada media sosial yang terus memindai momen demi momen dalam kehidupan, kita juga punya hak untuk melupakan serta memutuskan ingatan mana yang ingin terus kita rawat. Olehnya, tidak apa melakukan kurasi pada citra yang tidak kita inginkan di media sosial. Ya, tidak apa melakukan “pemangkasan” pada ruang yang menjadikan batas antara pujian dan kritik menjadi sumir. Kita punya kuasa untuk menentukan pilihan.












